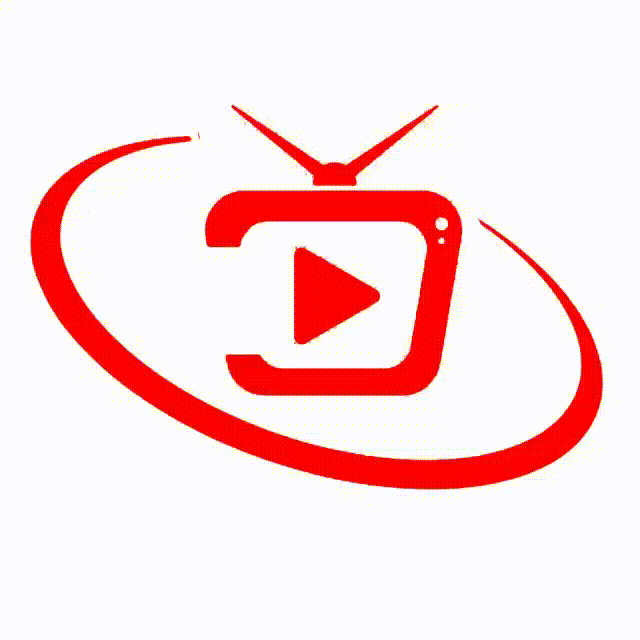Coba perhatikan baik-baik. Jika kita menempuh perjalanan dari arah Bandung menuju Purwokerto, atau sebaliknya. Kita bisa menemukan tempat di atas, yaitu sekitar tujuh kilometer di sebelah timur Terminal Wangon. Di situ terdapat pasar tradisional. Buka setiap pagi, dan menjelang siang, atau sekitar jam sembilan mulai terlihat sepi. Meskipun pasar itu terlihat kecil, namun pada waktu-waktu tertentu, jalanan di depan pasar ini memberi kontribusi cukup besar dalam menambah angka kemacetan di seantero tanah Jawa. Terutama saat-saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pasar ini berubah menjadi pasar tumpah, dan kendaraan bisa mengular sampai puluhan kilometer.
Baiklah, saya akan memulai memaparkannya dari seorang laki-laki yang berkulit hitam dan berambut lurus. Laki-laki yang kala itu berperawakan kekar dan gagah. Namun akhir-akhir ini tubuhnya nampak begitu layu. Guratan-guratan sekal pada kulit yang membungkus dagingnya pun mulai terlihat tipis, kisut, seperti kulit gayam—keriput. Tak banyak yang tahu tentang apa yang ada dalam pikirannya memang. Karena sepanjang hidupnya dia selalu tertutup dengan siapapun. Bukan lantaran sombong, atau tidak mau bergaul seperti orang kebanyakan. Tetapi—memang begitulah—dia lebih punya naluri ketimbang otaknya untuk berpikir. Sehingga, curhat pun seperti menjadi suatu yang tidak penting. Dan, yang ada hanyalah bekerja, bekerja, dan bekerja. Meskipun hanya sebagai kuli tukang panggul di pasar.
Untuk pertama kalinya saya melihat laki-laki ini: saat itu, usai saja wareng berteriak-teriak mendobrak pagi. Semburat jingga merekah, seiring kedua telapak kaki saya yang menapaki bibir-bibir parit, di sawah-sawah pinggiran desa. Saya berjalan melewati jalan pintas. Dari arah Pekuncen, memasuki Desa Kedung Ringin, Karang Benda, dan belok ke kiri. Tepatnya ke arah barat.
Dari balik tumpukan jerami yang menjulang kelangit, dan masih basah oleh sisa embun malam, laki-laki ini muncul. Ia berbaur diantara saya, dan orang-orang pejalan kaki. Orang-orang yang dengan aneka bawaan dalam gendongan serta pikulan: ada sayuran, kerupuk, gula merah, dan beberapa ekor unggas. Yang di belakangnya masih ada beberapa orang lagi, terus sampai tidak begitu terlihat jelas dari penglihatan saya. Dan, saya melihat laki-laki ini tidak seperti orang-orang yang lain. Ia hanya melenggang, tanpa barang bawaan. Lalu berkelabat, hilang dari pandangan saya.
Sebenarnya, sepanjang perjalanan itu, tidak begitu banyak yang saya pikirkan, apalagi tentang laki-laki ini. Kecuali, hanya membayangkan segelas kopi hangat, lembaran-lembaran tempe mendoan yang gurih—makanan khas Banyumas—yang menggoda pikiran saya untuk segera mengunyah, sebagai pengganjal perut yang sudah keroncongan.
Tak lamapun, sampailah saya di jalan besar. Tepatnya di sebuah pasar pagi yang saya maksud tadi, yaitu Pasar Thengok. Seperti harapan saya sebelumnya, saya langsung duduk di sebuah warung kecil, di sebelah emperan toko sekitar pasar. Memesan segelas kopi hangat, dan menyantap lembaran-lembaran tempe mendoan yang gurih dan nikmat itu. “Nyam..nyam..nyam. Hoooiik!” Sendawa, kekenyangan.
Tiba-tiba saya mendengar orang berteriak-teriak, ”Nakum! Nakum!” Suaranya keras, menandingi VCD bajakan yang digeber sampai kelaingit. Suara itu muncul dari mulut laki-laki gendut yang mengenakan celana komprang. Tak lamapun seorang laki-laki berkulit hitam, berambut lurus, dan berperawakan kekar menghampiri. Laki-laki ini adalah laki-laki yang saya lihat muncul dari tumpukan jerami, dan berjalan beriringan sejak memasuki desa Kedung Ringin. Ya, laki-laki yang tidak terlalu penting dalam pikiran saya tadi.
”Kum, bawa barang-barang saya ke pinggir jalan raya, cepat!” perintah si laki-laki gendut itu. Laki-laki yang disebut sebagai Nakum itu mengangguk, bergegas tanpa kata. Berkarung-karung terigu, kardus serta beberapa belanjaan habis dipanggulnya.
Tak lama kemudian, suara yang lain menyusul dengan kalimat dan nada yang sama, ”Nakum! Nakum!” Kali ini seorang ibu-ibu dengan rambut digelung seadanya. Saya melihat ibu-ibu itu kepayahan membawa barang belanjaan. ”Kum!” katanya ” Bawa belanjaan saya ke depan jalan raya, cepat!” lanjutnya. Nakum pun mengangguk, bergegas, tanpa komentar. Dan, dengan tangkas pula belanjaan-belanjaan itu habis dalam panggulannya.
Belumlah laki-laki ini sempat beristirahat barang sejenak, kembali suara itu berteriak-teriak seperti suara sebelumnya. ”Nakum! Nakum!” Dari sebelah kiri saya, sebelah kanan, di sudut dekat tukang tahu, dan di belakang tukang pecel. Semua berebut memanggil-manggil Nakum. Sungguh, sepertinya tak ada nama yang lain di tempat itu kecuali Nakum, Nakum, dan Nakum. Ya, nama ini begitu populer di pasar ini.
Dari situlah, laki-laki bernama Nakum ini mulai berputar-putar dalam pikiran saya. Bukan karena apa-apa, tapi karena heran. Ya, heran mengapa tenaga laki-laki ini begitu kuat? Bagai seekor kuda. Tanpa meringkik sedikitpun, ia memanggul barang-barang belanjaan orang-orang di pasar itu sampai habis. Manusia macam apa ini? Dari sejak pertama saya melihatnya—menapaki jalanan itu, hingga sampai ke pasar—tubuhnya tidak berhenti seperti robot. Entah, apa yang membuatnya begitu perkasa?
Saya masih duduk di warung tempat semula. Satu gelas kopi di hadapan saya, tinggal seperempat. Satu piring mendoan yang berukuran lebar, tinggal separuh. Hm.., kenyang sudah rasanya. Hooooiik!! Sayapun kembali bersendawa.
*
Pasar pun sudah terlihat sepi. Para pedagang, serta pembeli nyaris tak ada lagi. Kecuali warung yang sejak tadi saya singgahi, sertabeberapa toko yang memang masih buka sampai jam lima sore.
Laki-laki bernama Nakum itu luput dari pandangan saya. Tanya tentang ’ke mana laki-laki itu’ pun muncul dari pikiran dan benak saya. Sudah pulangkah, atau memang masih berada di sekitar pasar—bersembunyi menghitung penghasilan? Seiring itu pula, bola mata sayup saya berlarian ke setiap sudut tempat. Tak lain, dan tak bukan, manusia perkasa yang berotot sekal seperti kuda itu yang saya cari. Namun, sampai jelalatan mata saya ke sana-kemari, tidak juga menangkap keberadaannya. Akhirnya, sayapun memutuskan untuk tidak lagi mencari-cari , apalagi memikirkannya. Enggak penting kali!
Matahari pun mulai berpijar naik semakin ke atas. Hawa dingin yang sejak tadi pagi membalut sekujur tubuh saya juga telah berganti dengan hangat matahari yang menggerayangi planet bumi tempat saya berpijak. Jaket pun saya lepas. Gerah. Ya, saya merasakan butiran-butiran keringat mulai merembas dari dalam tubuh saya.
Untung saja segelas kopi hangat yang saya sruput mampu membantu mengganjal kedua bola mata saya, sehingga, saya masih bisa bertahan menahan rasa kantuk usai bergadang menyaksikan dari dekat, dan memotret ritual tahunan—nyadran—di sekitar pemakaman Prabu Wono Keling, Pekuncen, malam itu.
*
Entah, dari mana datangnya laki-laki Nakum ini, kok tiba-tiba saja ia sudah berada duduk tepat di samping sebelah saya.
Dengan handuk putih yang sudah kumal kecoklatan, ia mengusap keringat yang mengguyuri tubuhnya. Sambil nongkrong, Nakum memantik korek gasnya. Lalu menyalakan sebatang rokok yang sudah diapit kedua jarinya. Klepuus.., begitulah saya membayangkannya. Dari mulut Nakum mengeluarkan gumpalan-gumpalan asap putih yang sengaja ia mainkan dengan lidahnya: membentuk bulatan-bulatan seperti cincin, lalu buyar dihempas angin. Hm..nikmat sekali sepertinya.
Baru saja segelas kopi itu diletakkan dihadapan Nakum, tiba-tiba, samar-samar telinga saya menangkap suara anak seekor binatang.
”Cit..cit..cit..”
”Cit..cit..cit..”
Hm, binatang yang menurut saya, hewan kecil yang paling menjijikkan. Mahluk yang selalu mengganggu serta mengusik kehidupan manusia. Tidak pernah menanam, apa lagi ikut merawatnya. Tetapi di saat-saat menjelang panen, ia pula yang menggasak habis tanaman-tanaman itu. Tikus. Ya, suara itu suara bayi-bayi tikus.
Saya tidak tahu, dari mana arah suara itu? Padahal, sebelumnya saya tidak mendengar suara apa-apa, kecualai suara VCD bajakan, orang-orang yang tawar-menawar barang, memanggil-manggil nama Nakum, serta sendok yang berdenting beradu dengan gelas di tangan pemilik warung kopi. Atau, memang suara cemendil ini kalah tanding dibandingkan dengan suara-suara itu sebelumnya? Saya pun jadi bergidik.
Saya mencoba bergeser sedikit lebih dekat ke arah Nakum, untuk menghindari suara itu maksudnya. Tetapi, suara ini malah semakin jelas di telinga saya.
Tiba-tiba, bola mata saya terbelalak, seperti loncat keluar. Astaga! Ternyata binatang-binatang kecil kemerahan itu sudah berada digenggaman tangan laki-laki ini. Empat ekor. Ya, empat ekor. Satu-persatu dijinjing dengan jarinya. Sambil mendengak ke atas, ia masukkan pula cemendil-cemendil itu ke dalam mulut, dan masuk ke dalam perutnya.
Ini adalah kali pertama saya menyaksikan dengan mata dan kepala saya sendiri, seorang manusia menelan cemendil yang masih hidup seperti menelan bodrex. Saya tidak bisa membayangkan, bagaimana rasanya jika binatang-binatang itu meronta-ronta di dalam perutnya?
Hii..
Saya semakin tidak tahan melihatnya. Saya segera meraih tas punggung saya, lalu meloncat meninggalkan Nakum. Saya berlari ke arah jalan raya, menjauh dari tempat ini. Saking paniknya, saya sampai lupa membawa jaket saya. Lebih konyol lagi, saya juga lupa membayar segelas kop,i dan enam lembar tempe mendoan berukuran besar. Yang pada akhirnya, semua itu tak mampu bertahan dalam perut saya sampai proses pencernaan berakhir. Ya, saya muntah semuntah-muntahnya. Huwaakk! Berceceran sepanjang jalan. Menjijikkan sekali memang.
Dari situlah, sampai bertahun-tahun sudah saya kembali, dan menjalani hidup di Kota Jakarta ini, saya masih seringkali merasakan jijik, serta ingin muntah jika mengingatnya. Bukan saja karena teringat aksi Nakum di Pasar Thengok yang menelan cemendil tikus masih hidup itu. Melainkan karena banyaknya ’Manusia Tikus’ yang hidup, dan berkeliaran di kota ini. Ya, Manusia Tikus! Manusia-manusia yang menggasak uang rakyat, serta uang negara tanpa perasaan dan merasa bersalah.
Hii..! Huwaakk!
Lebih menjijikkan lagi bukan?
Tetapi, dari peristiwa itulah saya menjadi tahu, bahwa, ternyata, cemendil tikus yang masih hidup dipercaya oleh sebagian orang bisa dijadikan sebagai obat kuat.(*
Satelit Barat-Jakarta 201
PENULIS: Widi Hatmoko
______________________