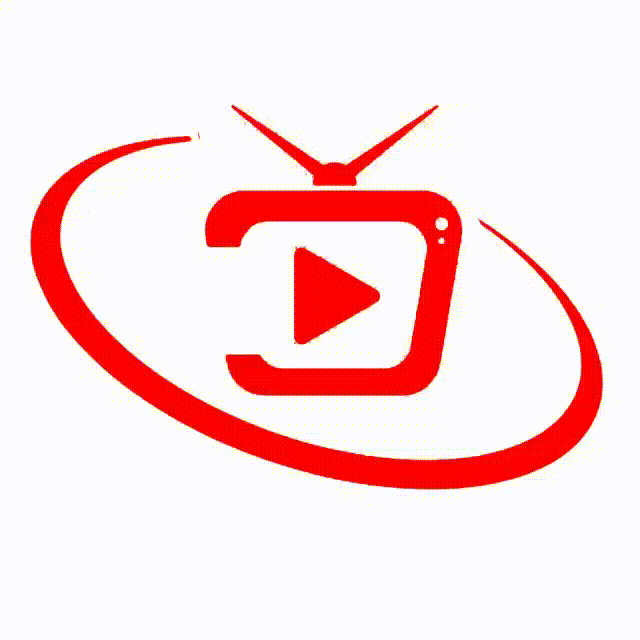Jika ada 1500 kendaraan yang antre dan berpikiran mereka merasa punya hak untuk jalan lebih dulu–sementara jalanan hanya muat dua kendaraan untuk saling berpapasan–maka bisa dibayangkan, yang terjadi adalah tumpukan kendaraan yang tak pernah terurai. Bahkan mustahil untuk terurai, bukan?

Jika ada 1500 kendaraan yang antre dan berpikiran mereka merasa punya hak untuk jalan lebih dulu–sementara jalanan hanya muat dua kendaraan untuk saling berpapasan–maka bisa dibayangkan, yang terjadi adalah tumpukan kendaraan yang tak pernah terurai. Bahkan mustahil untuk terurai, bukan?
Saya tak pernah menyangka, terjebak macet di jalanan itu bisa memberikan pengalaman sangat berharga. Adalah Bibit Winarno, seorang sopir taksi yang saya tumpangi yang telah memberikan pengalaman berharga itu.
Nama sopir taksi itu mudah sekali saya ingat, karena nama awalnya memiliki kesamaan dengan nama mantan wakil ketua sebuah lembaga anti korupsi yang kini tengah digandrungi, Bibit Samat Rianto; atau nama mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Sementara, nama belakang sopir taksi itu, mengingatkan saya pada penulis buku investigasi terkenal yang kini jadi host tayangan kuliner, Bondan Winarno.
Dari Bibit Winarno sang sopir taksi itu, saya mendapatkan pengalaman berharga yang mungkin sepele karena sudah lama akrab dengan keseharian kita.
Saat bunyi klakson terdengar sahut-sahutan, Bibit Winarno yang terlihat tenang di belakang kemudi hanya tersenyum. Sesekali lewat kaca spion, dia melihat ke arah saya yang tampak gelisah. Dia lantas berkata kepada saya yang sedang kesal dengan suasana kemacetan itu.
“Saya gak mau menyalakan klakson sembarangan,” katanya.
Saya hanya tersenyum kecut mendengarnya. Pikiran saya waktu itu berkata, “Apa pentingnya lo ngomongin klakson, Pak? Itu urusan lo. Yang gua mau sekarang gimana caranya gua harus keluar dari kemacetan.”
Namun, tiba-tiba saja saya tersentak ketika sopir tersebut melanjutkan kembali omongannya. Menurutnya, dia tak pernah mau menyalakan klakson sembarangan, karena dia tahu betul dirinya benci banget kalau denger orang nyalain klakson sembarangan. Karena itu, dia berpikiran, pasti orang lain juga merasakan hal yang sama jika dia membunyikan klakson sembarangan.
Pikiran saya yang sedang kesal dan beku saat itu, tiba-tiba saja langsung tenang dan mencair mendengar omongan Pak Bibit Winarno.
Saya langsung membayangkan, jika saja semua para pengemudi kendaraan di jalanan ini memiliki pikiran yang sama dengan Pak Bibit, maka takkan terjadi kemacetan, takkan terjadi keributan di jalanan, atau hal-hal negatif lainnya. Karena, semua orang sadar dirinya akan sakit jika disakiti. Lalu setelah kesadaran itu muncul, maka dia akan menolak menyakiti orang lain. Pada titik itu, maka takkan ada lagi sikap egoisme dan memaksakan kehendak sendiri.
Sikap yang ditunjukan sopir taksi tadi, dikemudian hari berhasil saya ketahui sebagai inti dari rasa welas asih, setelah saya membaca resensi buku “Compassion” yang ditulis Karen Armstrong.
Menurut Karen dalam resensi itu, inti dari kemanusiaan adalah kaidah emas, yakni berusaha melihat ke dalam diri sendiri untuk menemukan hal yang membuat kita sakit, lalu menolak dalam keadaan apapun untuk menimbulkan rasa sakit tersebut kepada orang lain. Atau berusaha memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan.
Konsep kemanusiaan itu adalah untuk menangkal ancaman intoleransi dalam kehidupan beragama sehari-hari. Kita bisa lihat bagaimana kelompok mayoritas di sekitar kita ternyata masih belum mampu memperlakukan minoritas seperti halnya bagian dari mayoritas itu.
Bahkan, dalam beberapa hari komunikasi saya dengan orang-orang yang dicitrakan khalayak jauh dari dosa, ternyata mereka masih dengan gampangnya menempelkan label “kafir” pada kelompok yang tak sekeyakinan dengannya. Bahkan dengan klaim kebeneran yang mereka yakini, mereka melarang pendosa untuk menyebut-nyebut nama Tuhan.
Saya teringat kembali tokoh Maria Zaitun dalam sajak Nyanyian Angsa karya almarhum Ws Rendra. Saya juga bertanya kepada kelompok yang jauh dari dosa itu, bagaimana jika posisi mereka berada dalam posisi kelompok yang mereka hujat sekarang??
Saya tak butuh jawaban mereka, karena sikap sopir taksi sudah jauh memberi jawaban dari yang saya perlukan selama ini. Memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan….(Rus)