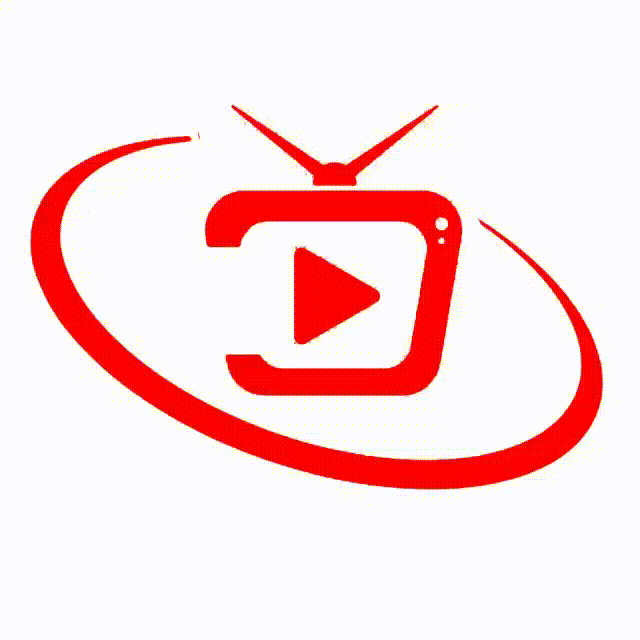Manusia adalah anak sang waktu. “Mereka yang tak dapat mengingat masa lalu akan dihukum mengulangi kesalahan yang sama.” Ungkapan George Santayana menjadi kalimat pembuka dalam sebuah ulasan politik yang ditulis pemikir kebangsaan dan kenegaraan, Yudi Latif di harian Kompas, dua tahun silam.
Baiklah, mari mengingat kembali masa lalu itu supaya kita tak dihukum untuk mengulangi kesalahan yang sama. Persisnya pada 28 Oktober 1928, ketika pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke berkumpul, lalu memproklamirkan: kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Apa yang melatarbelakangi para pemuda dan pemudi Indonesia sehingga harus memproklamirkan tiga ikrar tersebut?
Dalam diskusi yang digelar Lingkar Muda Indonesia (LMI) dan harian Kompas pada 26 November 2011, yang kemudian hasil diskusinya dituliskan dalam bentuk laporan di harian Kompas terbitan 29 November 2011, diketahui, bahwa sebuah bangsa tak lahir dari kekosongan. Dia lahir dari sebuah kebulatan tekad yang dibimbing oleh semacam utopia tertentu. Utopia mula-mula yang menggiring pembentukan “Indonesia” adalah kemerdekaan dari kolonialisme.
Kemerdekaan dari kolonialisme adalah sebentuk ikhtiar. Dalam laporan hasil diskusi itu disebutkan, ada nilai kebebasan dan keadilan dalam ikhtiar itu. Ketika semua jadi satu, tak ada lagi logika mayoritas-minoritas: yang ada hanya kesetaraan.
Mari kita berkaca kembali pada pengalaman masa lalu itu, bagaimana tiga ikrar dari Sumpah Pemuda mampu merepresentasikan anak bangsa dari bermacam-macam pulau dengan warna kulit dan bentuk wajah yang berbeda-beda, kemudian bersepakat untuk keluar dari belenggu kolonialisme.
Ada kesadaran kolektif yang muncul sebelum lahirnya Sumpah Pemuda itu. Kesadaran yang menyatakan bahwa kolonialisme yang menghisap segenap kekuatan sosial dan ekonomi harus dituntaskan sebab tanpa itu, sebuah bangsa tak pernah berdikari kecuali sebagai kaki tangan asing berkedok persemakmuran.
Jika membicarakan penghisapan segenap kekuatan sosial dan ekonomi, bukankah perilaku koruptif saat ini telah memberi dampak yang lebih dahsyat dibandingkan dengan kolonialisme pada jaman itu. Lalu, jika kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemilik kewenangan itu sudah merambah ke hampir seluruh seluruh sendi-sendi negara mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidakkah itu menandakan negeri dalam keadaan darurat?
Pemuda yang besar dalam kondisi bangsa yang memprihatinkan seperti sekarang ini, tak perlu lagi membuat sumpah yang serupa seperti ketika munculnya kesadaran menghilangkan kolonialisme dari bumi Indonesia.
Jika masih merasa dan ingin dianggap sebagai putra dan putri Indonesia yang bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia; maka pemuda dan pemudi Indonesia harus memulai dengan komitmen untuk memperbaiki bangsa ini.
Caranya, jika masih belum mampu menangkapi para koruptor dan menghentikan laku koruptif, maka pemuda dan pemudi Indonesia harus berani menolak untuk tidak melakukan kegiatan yang nol manfaat untuk rakyat. Apalagi jika sampai merugikan rakyat dan negara.
Ketika kemiskinan sudah nyata-nyata dipertontonkan di depan mata kita, kemunduran etos kerja ditunjukan dengan semakin suburnya peminta-minta di jalan raya, dan kesenjangan mendapatkan hak semakin terbuka, masihkah pemuda Indonesia menyikapinya dengan menggelar jalan santai dan seminar yang tak lebih dari “onani” karena gagasan-gagasan dalam sedminar tak pernah sampai menyentuh bumi (baca: kepentingan rakyat)?
Adalah sebuah ketololan yang sangat luar biasa, jika mereka yang mengatasnamakan organisasi pemuda yang secara nyata dibiaya oleh APBD/APBN, masih tanpa malu menggelar kegiatan yang tak membumi di tengah kondisi bangsa yang sudah disebutkan tadi.
Pemuda saat ini harus lebih kreatif dan progresif. Seperti apa yang disampaikan Romo Shindhunata, jangan mau didikte oleh keinginan alam bawah sadar yakni kebohongan, keserakahan, dan kepalsuan.
Tentu tak menjadi soal organisasi pemuda mendapatkan anggaran kegiatan dari APBD/APBN kemudian menggelar jalan santain dan seminar. Namun, sesuai dengan azas kepatutan, gunakanlah sebesar-besarnya untuk kegiatan yang lebih berdayaguna bagi masyarakat.
Maka, sebagai bentuk kesadaran bersama untuk keluar dari neokolonialisme yang ada di bumi pertiwi ini, pemuda yang demikian itulah layaklah untuk mengucapkan ikrar: kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia…..