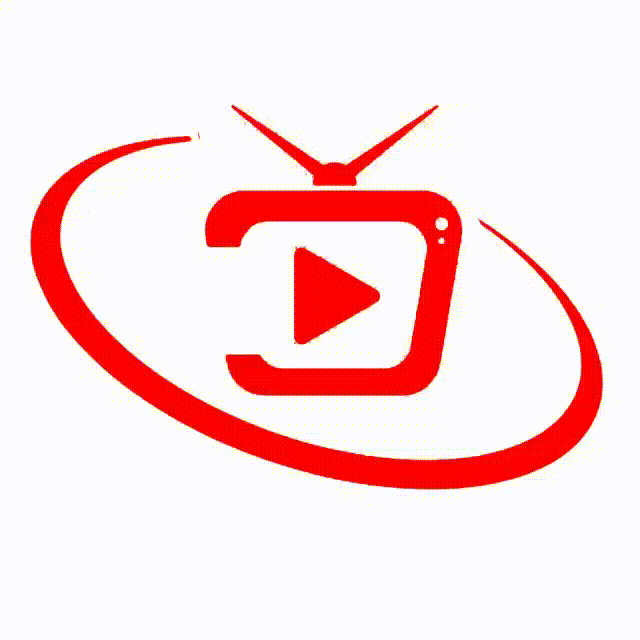Setelah masa pendaftaran calon berakhir kemarin, dapat dipastikan bahwa Pilkada serentak gelombang ketiga tahun 2018 ini bakal kembali diwarnai oleh hadirnya “kontestan” kotak kosong di panggung perhelatan. Angkanya bahkan naik dari 3 paslon (2015) dan 9 paslon (2017) menjadi 13 paslon. Ketiga belas daerah yang bakal menggelar Pilkada dengan calon tunggal vs kotak kosong itu adalah Kota Prabumulih (Sumsel), Kota Tangerang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang (Banten), Kabupaten Pasuruan (Jatim), Kabupaten Karanganyar (Jateng), Kabupaten Enrekang (Sulsel), Kabupaten Minahasa Tenggara (Sulut), Kabupaten Tapin (Kalsel), Kabupaten Puncak (Papua), Kabuaten Mamasa (Sulbar), Kabupaten Jayawijaya (Papua), dan Kabupaten Padang Lawas Utara (Sumut). Banten “hebat” : 3 atau 75% dari 4 daerah yang melaksanakan Pilkada.
Pilkada dengan calon tunggal telah melahirkan fenomena unik dalam sejarah pemilu dan kepolitikan lokal di Indonesia, yakni hadirnya kotak kosong di arena kontestasi. Secara normatif, fenomena ini dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 100/PUU-XIII/2015 yang intinya menyatakan Pasal 49 ayat (9) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan kepala daerah peserta pemilihan setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada satu pasangan calon.
Putusan MK itu, suka tidak suka, telah semakin mengokohkan hegemoni kapital dan para bandar dalam perhelatan Pilkada. Jika sebelum putusan itu terbit, para pemodal harus berhitung dan mengendalikan syahwatnya dalam borong-memborong parpol agar tidak sampai kebablasan, hingga jagonya maju tanpa lawan dan oleh karenanya Pilkada harus ditunda. Pasca putusan itu, kalkulasi dan syahwat borong-memborong parpol sama sekali tidak relevan lagi untuk mereka pertimbangkan. Di sisi lain, jalan pencalonan melalui jalur perseorangan semakin berat; dan hanya orang dengan “sedikit nekad” atau keterlanjuran saja yang akan tetap maju ke medan pertarungan.
Faktor pemicu
Di luar putusan MK sebagai pemicu dari sisi legal-juridis, lantas faktor apa sesungguhnya yang telah melahirkan fenomena kotak kosong pada perhelatan Pilkada? Bagaimana penjelasan sosio-politik atas fenomena paradoks ini? Pilkada yang didesain oleh para pengusung pendekatan new institusionalism sebagai jalan untuk mengonsolidasikan dan menumbuhkan demokrasi di aras lokal justru cenderung melayukannya sebelum berkembang. Paling tidak, sejumlah ruh demokrasi seperti kompetisi, kontestasi gagasan, dan pluralitas pilihan menjadi tiada.
Faktor pemicu pertama adalah soal high cost, biaya yang kelewat mahal. Komponen pembiayaannya sudah jadi rahasia umum, mulai dari mahar politik (politcal dowry), alat peraga sosalisasi dan kampanye, hingga ke anggaran untuk saksi. Ini yang oleh para elit parpol biasa disebut sebagai cost politics, ongkos politik. Pilkada langsung yang mulai digelar sejak 2005 silam, yang diharapkan akan melahirkan potensi-potensi kepemimpinan lokal yang genuine (orisinil), kompeten dan berintegritas, dalam praktiknya kemudian masih jauh panggang dari api. Demokrasi elektoral secara umum sudah dibajak dan dihegemoni oleh kekuatan modal semata-mata.
Itulah sebabnya, bahkan kader-kader internal parpol pun yang secara figuritas memiliki kompetensi, rekam jejak yang unggul, dan integritas dengan mudah bisa tersisih. Situasi ini kemudian “disempurnakan” oleh prosedur dan mekanisme pencalonan yang berat, baik bagi calon-calon yang maju melalui jalur parpol maupun perseorangan. Yang maju melalui parpol, regulasi yang memaksa parpol harus berkoalisi karena tidak memenuhi threshold syarat pengajuan bakal calon kerap menjadi alasan mengapa kemudian partai-partai akhirnya memilih untuk bergabung dalam koalisi besar yang diborong para pemodal, baik pendukung petahana maupun penantang baru.
Faktor kedua adalah lemahnya pelembagaan partai politik sebagai institusi yang berkewajiban menyiapkan kader-kader pemimpin sekaligus sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Ada banyak variabel untuk mengukur bagaimana pelembagaan parpol dilakukan. Di antaranya adalah proses penegasan ideologi (atau setidaknya platform ideologis) yang mestinya menjadi rujukan perilaku institusi termasuk dalam urusan pencalonan kepala daerah; demokratisasi internal, dan fighting spirit untuk maju dan memperjuangkan kader sekaligus pilihan visi misi dan programnya bagi daerah setempat. Di daerah-daerah dengan calon tunggal mengisyaratkan bahwa variabel-variabel ini sangat lemah.
Maka tidak mengherankan jika partai A yang sepanjang tahun mengkampanyekan gerakan antikorupsi, pada saat musim Pilkada kemudian merapat pada koalisi yang dipimpin oleh partai yang elit-elitnya belepotan dengan kasus rasuah. Pun tidak aneh, jika partai B yang kabarnya memiliki platform sebagai partai Islam, pada musim Pilkada berkongsi dengan partai yang secara ideologis sama sekali tidak beririsan. Kok bisa? Karena ideologi atau platform partai yang mestinya menjadi barang suci bagi partai politik sudah lama dikesampingkan. Jadi kalau masih ada partai yang teriak-teriak pentingnya memperjuangkan ideologi hari ini, itu sejenis “hoax” spesies baru !
Faktor ketiga adalah lemahnya local civil society vis a vis kekuasaan yang hegemonik.Setiap kali memasuki musim perhelatan pilkada elemen masyarakat sipil (di luar partai politik yang sudah lumpuh layu tentunya) seperti aktifis LSM, mahasiswa, dan kalangan cendekia, pada umumnya praktis hanya menjadi kerumunan, buih yang dengan gampang dikooptasi oleh kekuasaan. Gagasan bahwa kelompok masyarakat sipil diasumsikan bisa menjadi penyeimbang yang kritis bagi kekuasaan sekaligus sparing partner bagi partai politik dan pendidik politik yang berintegritas bagi masyarakat (pemilih) pada umumnya, idem ditto, ini juga spesies baru “hoax” zaman now.
Faktor terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah dominasi petahana dan/atau bandar yang membackup petahana. Kenapa disebut terakhir, karena berbeda dengan ketiga faktor diatas, soal dominasi petahana bukanlah urusan yang berhak disesali. Terutama jika dominasinya itu diperoleh secara alamiah karena prestasi kepemimpinannya, atau jika dominasi itu bersumber pada kekuatan materil yang diperolehnya dengan cara legal dan halal. Menjadi masalah dan layak dikritisi, bahkan disudahi, jika dominasi itu diperolehnya dengan cara-cara yang tidak legal, jauh dari halal, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi universal. Sebut saja misalnya jika dominasi itu ditopang oleh politik kekerasan, ancaman kekerasan; atau dominasi yang ditopang oleh kekuatannya bagi-bagi proyek (jika petahana) dengan cara-cara yang sarat kolusi dan nepotisme.
Bagaimana dengan borong-memborong partai ? Apakah melanggar prinsip demokrasi, ilegal dan jauh dari halal? Peraturan perundangan Pilkada sangat lugas, bahwa menerima imbalan atau meminta mahar politik diancam pidana 6 tahun penjara. Artinya komplit: itu rasuah (suap dalam kosakata syar’i), ilegal karena melanggar undang-undang, sekaligus mencenderai proses demokrasi elektoral. Masalahnya kemudian, semua orang sadar belaka, mahar politik itu kurang lebih sama dengan money politics, sama-sama mirip (mohon maaf) kentut yang keluar dari perut busuk : ghaib, tapi baunya menyengat!
Penulis adalah Agus Sutisna, Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang