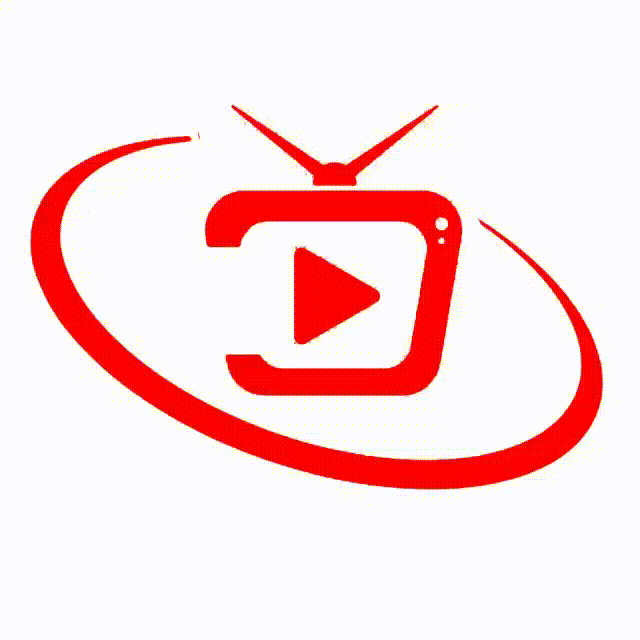Siang nanti, Rumah Dunia akan menggelar diskusi buku “Dinasti Banten” (Ade Irawan dkk). Beberapa waktu lalu saya ditawari Kang Golagong New untuk menjadi salah satu pembahasnya. Saya bersedia dengan catatan : Rano clear berpasangan dengan Jaman. Tapi sampai kemarin tandem Rano masih misterius. Namun begitu saya tetap ingin hadir. Sayangnya ada beberapa fardu kifayah yang harus saya tunaikan hari ini di kampus. Nah, tulisan lama ini (terbit April 2016 lalu di Kabar Banten) saya publish kembali sbg “catatan muhibah” untuk esensi semangat dan gagasan diskusi buku itu, dan tentu saja bentuk partisipasi saya meski in absentia. Selamat berdiskusi…
==========================================================================================
Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, diskursus tentang dinasti politik praktis berakhir jika gejala dinasti politik dilihat dan difahami secara simplistik dalam konteks norma hukum belaka sebagaimana para hakim MK melihat dan memahaminya, dan menegasikan konteks praksis sosiopolitik dimana dinasti itu hidup sebagai bentuk operasi kekuasaan.
Dalam amar putusannya, MK berpendapat bahwa Pasal 7 huruf r yang mengatur tentang syarat pencalonan, dimana dinyatakan bahwa calon kepala daerah tidak boleh ada konflik kepentingan dengan petahana, yakni gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, maupun wali kota dan wakil wali kota yang masih memegang jabatan, bertentangan dengan Pasal 28 i ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Pasal 7 huruf r UU Pilkada 2015 dianggap diskriminatif dan dengan demikian melanggar hak azasi manusia.
MK menafikan fakta-fakta sosiopolitik bahwa praktik dinasti telah membawa implikasi buruk yang meluas dalam kehidupan masyarakat, bertentangan dengan cita-cita luhur reformasi, kontraproduktif terhadap kebutuhan memperkuat demokrasi substansif, serta mendistorsi pesan-pesan mulia yang terkandung dalam prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi.
Dalam kasus Pilgub Banten 2017, selain karena alasan tersebut diatas, perbincangan dinasti politik juga menjadi tidak relevan jika gejala dinasti hanya dilihat dan difahami dengan merujuk kepada pandangan para ilmuwan politik yang memberikan batasan pemahaman terhadap dinasti hanya dalam kerangka adanya praktik pewarisan (langsung atau melalui proses elektorasi). Dalam pemahaman demikian, saat ini tidak ada satupun figur bakal calon yang tersangkut kasus dinasti, bahkan juga Andika dan Jaman. Karena Ratu Atut, ibunda Andika sekaligus kakaknya Jaman, tidak lagi dalam posisi sebagai gubernur Banten. Rantai estafeta kekuasaan dari Atut ke Andika atau Jaman sedang terputus. Jadi posisi mereka berdua sama saja dengan WH, Anton, JB, Aeng, Eden, Tantowi, Marissa dan Soleh Majid (aktifis Lebak yang berminat maju dan sudah mulai selfi-selfi bersama timsesnya di alun-alun Rangkasbitung).
Dinastokrasi berdiaspora
Tetapi isu dinastokrasi akan tetap relevan dan penting dipersoalkan oleh sebab fakta-fakta fenomenologisnya bahwa ia, khususnya di Banten, telah mengalami proliferasi (berdiaspora, menyebar) di banyak ranah kehidupan masyarakat, meski estafeta kekuasaan dinastik saat ini sedang terputus. Lantas, mengapa ia harus ditolak ? Tentu saja ditolak dalam pengertian sosiopolitik, bukan dalam konteks hukum. Sebab putusan MK bersifat final and binding (akhir dan mengikat).
Pertama, dinastokrasi paradoks dengan ikhtiar bangsa ini untuk mengkonsolidasikan demokrasi deliberatif, dimana ruang partisipasi harus dibuka seluas dan selebar mungkin bagi setiap warga. Dinastokrasi mempersempit peluang bagi kemungkinan hadirnya calon-calon pemimpin yang unggul integritas dan kompetensi terutama di daerah lantaran pintu masuk ke arena kontestasi kekuasaan didominasi oleh trah dan jaringan keluarga dan kerabat dinasti. Situasi ini sudah barang pasti merugikan masyarakat yang sejatinya menghendaki perubahan dan pembaruan tata kehidupannya dari waktu ke waktu. Padahal naluri purba kekuasaan cenderung konservatif, pro-kemapanan, bahkan anti-perubahan. Naluri model ini menjadi absolut di tangan dinastokrasi.
Kedua, dinastokrasi menyuburkan oligarki dimana operasi kekuasaan hanya didominasi oleh pikiran, ambisi dan kepentingan segelintir aktor politik di lingkaran dinasti dan para kroninya. Situasi ini buruk dilihat dari sisi kebutuhan melahirkan produk-produk kebijakan publik yang mewakili semangat dan aspirasi masyarakat luas. Gejala oligarkis juga dengan mudah dapat menegasikan prinsip-prinsip mekanisme check and balances diantara cabang-cabang kekuasaan. Maka tidak mengherankan jika berbagai macam proyek misalnya, diukur dari sisi manapun, lebih mencerminkan pemenuhan kepentingan pribadi, kroni dan kelompok ketimbang kepentingan warga.
Ketiga, dinastokrasi, terlebih lagi jika gejala-gejala faktualnya sudah merambah (berdiaspora) ke berbagai arena kehidupan publik (bisnis, sosial, pendidikan, keagamaan, pemuda dll) cenderung menyuburkan perilaku dan budaya koruptif, kolutif dan nepotistik yang sangat kental. Prinsip-prinsip luhur tatakelola kekuasaan dan governance seperti integritas, profesionalitas, meritokritas dan sejenisnya sama sekali tidak populer dalam tradisi yang dibangun dan dikembangkan oleh dinastokrasi, siapa pun yang mengaktori dan menjadi kroninya.
Keempat, berbagai riset menunjukkan bahwa dinastokrasi selalu bersitemali kuat dengan nafsu penguasaan atas aset-aset dan resources negara/daerah (Dal Bo, Snyder, Thompson, Sidel, Migdal, Okamoto, Hamid, dll). Karena dengan memaksimalkan penggunaan secara tak halal dan jauh dari prinsip keadilan aset dan rosources itulah pula dinasti dirawat dan dikembangkan, kemudian terus beranak-pinak. Dinastokrasi, seperti disimpulkan banyak peneliti, pada umumnya dimana-mana gejalanya sebangun : melahirkan para bandit yang memeras dan predator yang menguras kekayaan negara/daearah.
Kelima, hipotesa penulis, ke depan dinastokrasi akan menumbuh-suburkan mindset publik (khususnya generasi muda) yang tidak sehat, yang dengan mudah bisa dideteksi dalam ragam ekspresi dan artikulasi budaya serba instan; mentalitas pragmatis dan oportunis; culas dan khianat; tak menganggap penting integritas, kejujuran dan keluhuran akal budi dan sejenisnya.
Nah, dengan deretan implikasi buruk itu : anti-demokrasi; oligarki yang super egois; perilaku koruptif, kolutif dan nepotistik; rezim bandit dan predator; serta racun mindset bagi generasi muda, naif rasanya jika orang Banten masih rela memberikan pijakan bagi keberlanjutan tradisi dinastokrasi pasca Pilgub 2017 mendatang.
Penulis adalah Agus Sutisna dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT)