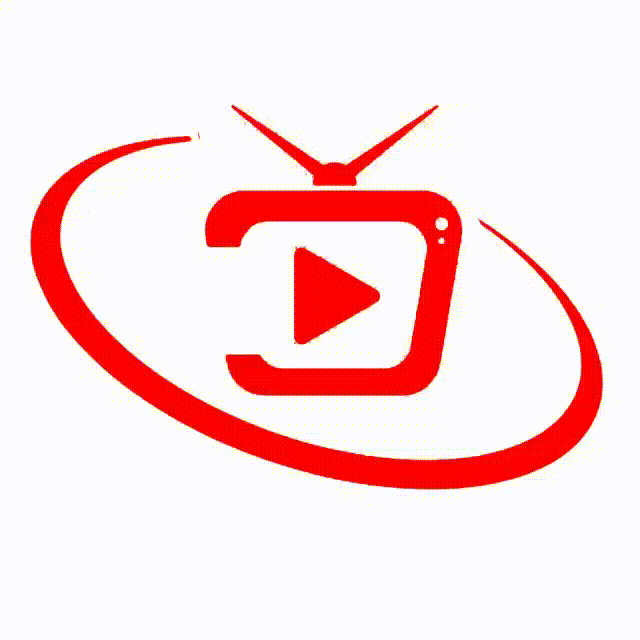Menjadi wanita seutuhnya di tengah masyarakat patriarki, adalah keniscayaan, sekaligus sebuah jalan panjang. Perempuan-perempuan di belahan dunia mana pun sepakat, peran lelaki dan perempuan saat ini, tak bisa lagi didasarkan pada gender.
Meski pada kenyataan, pola relasi lelaki dan perempuan—salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat—membentuk dominasi peran lelaki atas perempuan.
Yang menarik untuk dikaji, adalah peran perempuan-perempuan dalam kisah epik Mahabharata, kitab terpanjang di dunia milik masyarakat India yang dikagumi warga di pelbagai negara seantero jagad raya.
Kavita A Sharma, seorang cendekiawati masyhur di India, dalam bukunya “The Queens of Mahabharata” yang diterjemahkan di Indonesia menjadi “Perempuan-Perempuan Mahabharata”, menegaskan peran sentral para perempuan dalam cerita tersebut.
Di balik cerita kejayaan para Pandawa: Yudistira dengan kehebatannya memimpin negara, Bima dengan kekuataanya yang maha dahsyat, Arjuna dengan keelokan dan kemampuan melemahkan lawan politik—di samping juga kesaktiannya—juga, kehebatan Nakula dan Sadewa, ternyata ada peran penting seorang Kunti dan Drupadi.
Diceritakan dalam kisah itu, pada berbagai peristiwa, para lelaki justru cenderung peragu dalam bersikap. “Tidak seperti kaum perempuan, mereka tergagap-gagap ketika berhadapan dengan momen-momen penting,” tulis Kavita.
Yudistira misalnya, ketika dia kalah bermain dadu dari Kurawa dan harus menyerahkan seluruh kekuasaan Pandawa di Hastinapura—termasuk isterinya, Drupadi—hanya diam seribu bahasa tanpa sikap.
Meski permainan dadu tersebut atas siasat licik Sengkuni yang mengendalikan Kurawa, namun Yudistira mematung tanpa pembelaan, pun ketika isterinya, Drupadi dipermalukan di depan khalayak atas kekalahan taruhan itu. Pada saat itu, justru Drupadi sendirilah yang mengambil momen penting, dengan mempertanyakan standar etik para majelis di Hastinapura.
Tak hanya itu, Kunti dan Drupadi adalah perempuan yang selalu “mengemong” para Pandawa. Bahkan, dalam sebuah laku silih tapa di pengasingan, Kunti dan Drupadi secara nyata telah mengajarkan tata kenegaraan kepada Pandawa.
Selain Kunti dan Drupadi, ada sosok Amba yang melawan “dogma” dan memperjuangkan sikap seorang perempuan di tengah derasnya pengaruh kaum lelaki di negeri itu. Amba melakukan protes atas sayembara yang dilakukan oleh ayahnya Prabu Dharmahumbara.
Dalam sayembara memperebutkan tiga putri cantik Prabu Dharmahumbara: Amba, Ambika, dan Ambalika—yang dimenangkan Bhisma—Amba, menyatakan penolakan atas hasil sayembara tersebut. Sesuatu yang lancang dan tak pernah terjadi sebelumnya. Hanya karena sudah terpikat hati dengan Salwa, Amba menolak untuk dipersembahkan oleh Bhisma, meski Bhisma sudah memenangi pertarungan secara adil.
Sikap Amba dalam konteks kekinian adalah sebagai emansipasi. Pada kata emansipasi, Indonesia lekat dengan Kartini, seorang tokoh perempuan pejuang kesetaraan.
Dalam sebuah surat yang ditulis Kartini untuk sahabatnya di Amsterdam, E.H. Zeehandelaar tertanggal 25 Mei 1899, Kartini menuliskan sikap yang pada saat itu mungkin dianggap sebagai lancang:
“….mengenai pernikahan sendiri, aduh, azab sengsara adalah ungkapan yang terlampau halus untuk menggambarkannya! Bagaimana pernikahan dapat membawa kebahagiaan, jika hukumnya dibuat untuk semua lelaki dan tidak ada untuk wanita? Kalau hukum dan pendidikan hanya untuk lelaki? Apakah itu berarti ia boleh melakukan segala sesuatunya?….”
Pada usia 16 tahun, adalah titik kemenangan perjuangan Kartini. Dia merasa bebas dari “penjara” setelah menikah pada usia 12 tahun dengan seorang lelaki pilihan orang tua, yang tak pernah dikenalnya.
Namun, kebebasan secara pribadi Kartini bukanlah merupakan kepuasan. Kartini bertekad untuk berjuang bagi masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan sesama.
Di tengah deras semangat memperjuangkan hak sebagai seorang perempuan, Kartini tak lantas melupakan kewajiban untuk mencintai kedua orang tuanya. Dibanding kewajiban harus hormat sama adat istiadat, sikap kecintaan kepada kedua orang tuanyalah yang membuat Kartini menjadi seorang yang patuh saat itu.
Tentang pernikahan—di tengah penentangannya atas pernikahan yang dipaksakan—Kartini juga tak lantas antipati pada pernikahan. Kartini menuliskan, “… Akan tetapi, kami memang harus menikah. Tidak menikah merupakan dosa terbesar bagi wanita Islam. Aib terbesar yang akan ditanggung gadis bumiputera dan keluarganya….”
Sikap Kartini adalah seturut apa yang dilakukan perempuan-perempuan Mahabharata dalam cerita di atas. Meski mereka menguasai dan menjadi kendali atas para lelaki, perempuan-perempuan itu taat pada dharma. Bahwa seseorang boleh melepaskan seluruh ikatan dunia, kecuali moralitas….